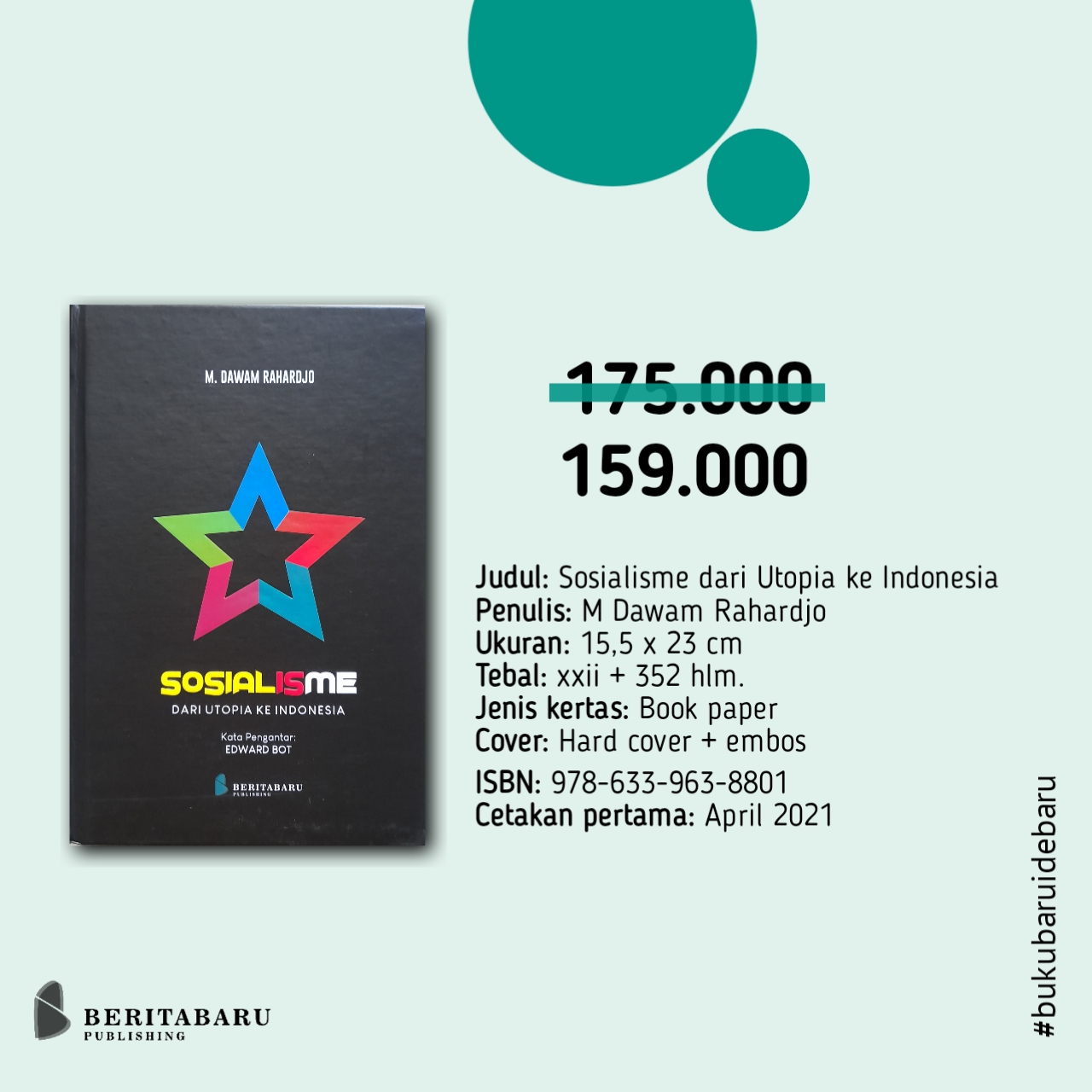Mengelola Transisi Mahasiswa Baru: Tanggung Jawab Institusi, Bukan Hanya Individu
Oleh: Mujib
Dosen Politeknik Negeri Pontianak
Setiap tahun, kampus di Indonesia baik negeri maupun swasta menerima ratusan ribu mahasiswa baru. Akan tetapi, data dari berbagai kampus menunjukkan bahwa tidak sedikit dari mahasiswa baru mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri. Sebagian besar institusi pendidikan tinggi masih menempatkan kesulitan dalam penyesuaian diri sebagai masalah pribadi mahasiswa. Padahal, jika dilihat dari perspektif kelembagaan dan tata kelola pendidikan, masalah ini justru menunjukkan adanya celah dalam sistem pendampingan dan kebijakan internal kampus.
Melalui penelitian yang saya lakukan di Program Studi D4 Teknik Mesin Politeknik Negeri Pontianak, ditemukan bahwa penyesuaian diri mahasiswa baru sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional mereka. Fakta ini sejalan dengan berbagai literatur yang menegaskan bahwa transisi dari jenjang sekolah menengah atas (SMA) ke pendidikan tinggi bukan hanya sekedar perubahan akademik semata, akan tetapi juga terjadi perubahan identitas sosial, lingkungan hidup, serta cara pandang terhadap dunia.
Namun demikian, menempatkan sepenuhnya beban penyesuaian diri pada mahasiswa tanpa adanya dukungan yang baik dari sistem dan strategi kelembagaan yang memadai merupakan bentuk pengabaian secara institusional. Pendidikan tinggi bukan hanya ruang akademik, tetapi juga merupakan sistem pelayanan publik. Dan seperti halnya pelayanan publik pada umumnya, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana lembaga menyusun kebijakan dan menciptakan ekosistem yang mendukung proses pendidikan.
Mengubah Paradigma Pengelolaan Mahasiswa Baru
Saat ini, sebagian besar kampus masih mengandalkan masa orientasi mahasiswa baru sebagai satu-satunya bentuk pendampingan mahasiswa baru. Kegiatan ini, meskipun memiliki manfaat sebagai pengenalan kehidupan kampus, secara umum hanya bersifat seremonial serta belum cukup menyentuh aspek psikososial mahasiswa baru. Setelah kegiatan orientasi selesai, mahasiswa langsung “dilepas” begitu saja ke dunia akademik yang penuh tekanan, tanpa sistem monitoring yang berkelanjutan.
Sebagai institusi sektor publik, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengelola proses transisi mahasiswa secara sistematis dan berkesinambungan. Pola pendekatan ini tidak hanya menguntungkan mahasiswa, namun juga dapat meningkatkan kinerja kelembagaan dalam jangka waktu panjang: menurunkan angka putus kuliah, meningkatkan retensi, serta membentuk lulusan yang lebih stabil secara emosional dan sosial.
Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, diantaranya adalah pertama membentuk unit layanan transisi mahasiswa baru yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat konseling, namun juga menjadi pusat koordinasi lintas unit antara lain dosen wali, BEM, organisasi kemahasiswaan, hingga unit karier mahasiswa. Kedua mewajibkan program pembinaan karakter, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosal dalam 6 bulan pertama masa kuliah, dengan pendekatan reflektif, praktikal, dan berbasis pengalaman nyata. Ketiga melatih dosen sebagai mentor penyesuaian diri, bukan hanya sebagai pengampu mata kuliah, namun dosen juga diharapkan peka terhadap dinamika psikologis mahasiswa lebih khusus mahasiswa baru.
Kolaborasi dan Kepemimpinan Institusional
Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan penyesuaian diri mahasiswa khususnya mahasiswa baru bukanlah hasil kerja salah satu pihak, melainkan kolaborasi antar unit di dalam perguruan tinggi. Mulai dari jurusan, lembaga kemahasiswaan, hingga biro administrasi, seluruhnya perlu senantiasa berjalan dalam irama yang sama. Pada titik ini kepemimpinan transformatif menjadi penting dalam institusi pendidikan tinggi.
Seorang rektor, direktur, dekan, atau ketua jurusan tidak cukup hanya menjadi seorang manajer administratif. Akan tetapi, mereka harus menjadi motor penggerak budaya kelembagaan yang berpihak pada mahasiswa. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam administrasi publik modern yakni responsivitas, transparansi, dan orientasi pada pelayanan yang humanis.
Dalam konteks pendidikan tinggi vokasi seperti politeknik, kebutuhan akan pola pendekatan ini bahkan lebih mendesak. Mahasiswa vokasi cenderung berasal dari latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga yang lebih beragam, sehingga tantangan penyesuaian diri mereka menjadi lebih kompleks. Kurikulum yang padat dengan kegiatan praktik juga menuntut kesiapan mental mahasiswa yang lebih prima. Tanpa adanya sistem pendampingan yang kuat, mereka bisa merasa tertinggal dan terpinggirkan sejak awal proses pembelajaran.
Peran Negara dalam Pendidikan yang Mengasuh
Pendidikan adalah salah satu layanan publik dasar yang harus disediakan negara. Oleh karena itu, negara haru hadir melalui institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi, agar tidak abai dalam proses menghadirkan pelayanan pendidikan tinggi yang peduli terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswanya. Jika negara dituntut menyediakan layanan kesehatan yang ramah pasien atau layanan administrasi kependudukan yang ramah warga, maka sudah seharusnya pendidikan tinggi juga menyediakan layanan pendidikan yang ramah terhadap mahasiswa baru.
Membantu mahasiswa menyesuaikan diri bukan hanya sekadar kegiatan sosial, melainkan intervensi kebijakan yang sangat strategis. Jika sejak awal mahasiswa merasa mendapatkan dukungan, diterima, dan dipahami, maka mereka akan tumbuh menjadi lulusan yang tidak hanya cerdas secara teknis akademik, namun juga matang secara emosional dan sosial. Dan pada akhirnya, inilah tujuan utama dari proses pendidikan tinggi yakni membentuk manusia paripurna, bukan sekadar pencetak ijazah.

 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co Gubuktulis.com
Gubuktulis.com surau.co
surau.co