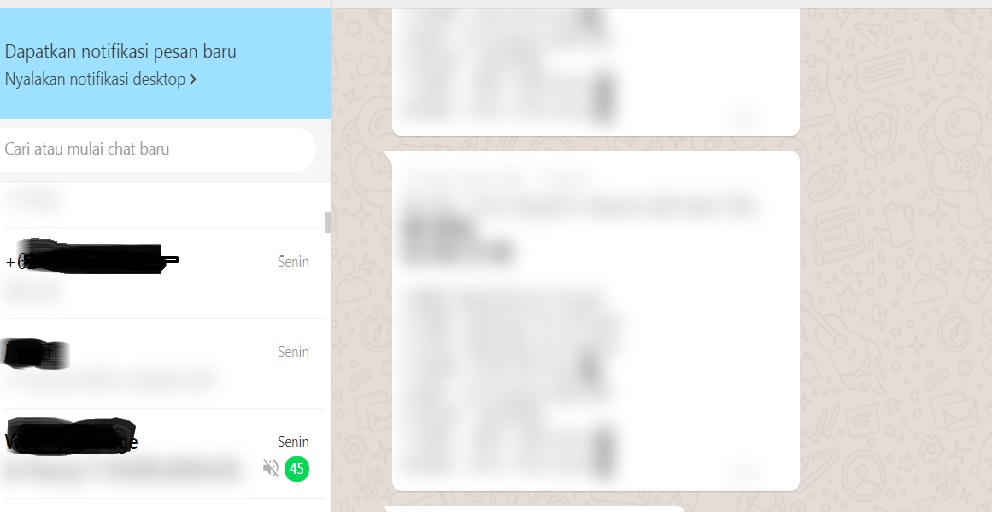Mencari Kunci Aura | Cerpen Sriwiyanti
Mereka bilang, Tuhan itu Maha Adil, menggilir tangis dan tawa sesuai porsinya. Tapi, bagaimana jika kamu mengenal seseorang yang tak pernah bahagia selama hidupnya. Dialah Sulastri, guru TK yang ketika menyanyikan lagu Jika Kau Suka Hati wajahnya ditekuk. Aku bukannya sok tahu tentang kehidupan Sulastri, dialah yang mengadu sendiri padaku. Mengatakan bahwa dia memang terlahir untuk menangis.
Jujur saja, kadang aku merasa Sulastri sedikit aneh. Dia perempuan yang berpendidikan, lulus kuliah PGTK dengan nilai baik, Sulastri juga punya keluarga yang hangat. Bahkan kalau diperhatikan, Sulastri lumayan cantik, meski hingga saat ini belum ada pria yang tertarik. Oh, pernah satu kali, tukang kebun beristri di sekolah tempat ia mengajar. Lekas ia tolak mentah-mentah pria beranak tiga itu. Lalu membrondongnya dengan sumpah-serapah.
Setiap hari Minggu, Sulastri datang ke rumahku. Kami duduk di teras menghadap bunga-bunga di halaman. Beberapa ekor ayam mengais-ngais serangga di dalam pot, hingga tanah berserakan dan akar bugenvil merah muda seperti tercerabut. Kuusir ayam itu dengan sapu ijuk, mereka berlari tunggang-langgang. Aku menyuguhi Sulastri dua gelas teh dan sepiring biskuit kelapa. Tak lupa kotak tisu yang kusiapkan di atas nampan. Benar saja, bahu Sulastri tiba-tiba berguncang.
“Kenapa, Sulastri?” suaraku tercekat, aku selalu ragu mengajak orang yang tengah menangis untuk bicara.
“Kamu tahu, Hartini? Dia mau menikah minggu depan. Pasti kamu sudah terima undangannya kan?”
“Iya, sudah. Tapi aku engga mungkin pergi dengan kondisi seperti ini.” Aku menunjuk kupluk yang menutupi kepala tanpa sehelai rambut.
“Kenapa semua orang bisa bahagia, punya banyak teman, pekerjaan yang layak, menikah, punya anak, senang-senang.” Setetes air mata kembali jatuh di tulang pipi Sulastri, lalu menetes di ujung dagu.
Aku menyerahkan selembar tisu sembari menepuk pundaknya yang tebal, “Semua orang punya jalan bahagia masing-masing, Sulastri.”
“Kecuali aku, lihat saja! Semua teman kuliah kita dulu, teman kerjaku sekarang. Mereka bahagia, punya suami, atau paling tidak mereka punya pacar. Aku bosan begini! Lihat, Syifa, Siti, mereka punya jalan hidup yang bagus.” Sulastri menghentikan ucapannya dengan isak yang panjang. Lalu hening, tangisnya tiba-tiba terhenti, air matanya tak lagi mengalir. “Aku pulang saja.”
Sesaat aku terdiam memandangi punggung Sulastri yang menjauh. Aku sendiri heran mengapa pertemananku begitu langgeng dengan Sulastri, jika dihitung sejak awal kuliah berarti sudah sepuluh tahun aku melewati akhir pekan dalam kubangan air matanya. Kutatap kelopak bugenvil yang jatuh di tanah. Aku berjalan meraihnya. Hari-hariku hanyalah milik bunga-bunga di taman ini, dan tentu saja Sulastri.
Pada Minggu pagi berikutnya, terdengar suara motor berhenti di halaman rumah. Aku menyibak gorden jendela kamar, kulihat Sulastri mengenakan setelan olahraga berwarna cerah, lengkap dengan sepatu kets, bertolak belakang dengan raut wajahnya.
“Fitri lulus kuliah,” hanya itu kalimat yang keluar dari mulut Sulastri. Fitri adalah adik Sulastri satu-satunya.
“Syukurlah, lulus tepat waktu. Engga kayak zaman kita dulu ya, mahasiswa sibuk demo.” Aku tekekeh sambil mengenang.
Baca Juga: Persepsi cerpen sriwiyanti
“Dia pasti langsung ditawarin posisi bagus sama omku di perusahaannya. Dia kan jurusan ekonomi. Engga kayak aku, PGTK. Engga ada gunanya!” satu tarikan nafas panjang mengakhiri kalimat Sulastri.
Aku mendekatkan segelas es teh padanya, “Bukannya bagus ya kalau adikmu langsung dapat kerja, kamu dan orang tuamu engga repot.”
“Aku muak! Hidup kok begini amat, selalu jadi figuran!”
Mendengar teriakan Sulastri, aku memilih diam, membiarkannya menghabiskan tisu di dalam kotak, juga segelas es teh yang kuhidangkan. Ketika tandas, Sulastri pamit dengan wajah sembap. Sebelum ia menyalakan motor bututnya, aku meminta Sulastri menemani ke dokter pada hari Senin esok. Dia sebenarnya sudah terbiasa menemaniku sebulan sekali, sebab aku tak punya siapa-siapa lagi.
Keesokan harinya, Sulastri datang terlambat dari kesepakatan. “Aku lagi sial, anak murid di kelasku berak di celana. Aku kena cipratan beraknya dan harus pulang ganti baju dulu.” ia menggerutu sepanjang jalan. Aku hanya manggut-manggut menahan tawa, membayangkan wajah Sulastri yang mirip seperti Bomb di film Angry Birds.
Ketika tiba di rumah sakit, aku masuk ke ruang dokter. Tak sampai setengah jam, aku buru-buru keluar karena firasatku tak enak, aku mengitari rumah sakit mencari Sulastri yang telah lenyap. Karena khawatir, aku memesan taksi menuju rumah Sulastri. Ketika kubuka pintu kamarnya, Sulastri sedang menangis.
“Kenapa?” kusentuh bahunya pelan.
Sulastri menepis tanganku lalu menenggelamkan mukanya di bantal. “Kamu engga lihat tadi, ada ibu-ibu di sebelahku yang mengira aku sedang mengantar anakku berobat? Memangnya wajahku terlihat tua sampai mengira aku ibumu?”
“Mungkin si ibu rabun dekat, atau badanku yang memang sudah kurus banget, pakai kupluk pula.” Aku menahan tawa demi menjaga perasaan Sulastri. Lalu berpamitan setelah yakin Bomb tidak meledak saat itu.
Pada hari Minggu berikutnya, Sulastri kembali datang. Ia menggunakan kebaya dan tas pesta. Bedak tebalnya luntur oleh keringat. Gincu merah muda dan sapuan blash on masih tersisa tipis.
“Aku menyesal menghadiri undangan anak kepala sekolah. Teman-teman guru yang lain datang sama suami dan anak. Aku duduk sendiri di pojokan kayak orang hilang. Di baris depanku ada mbak-mbak yang berbisik sambil melirik-lirik. Aku engga nyaman banget, aku lihat wajahku di spion. Engga ada yang salah, kecuali aku gendutan, pipiku nyempluk, sama sekali tidak menggemaskan.” Sulastri membanting tubuhnya di sofa. Aku hanya diam, menyodorkan segelas air es.
“Kita rapikan daun tanaman yuk, biar kamu bisa katarsis.” Aku menyerahkan gunting setelah ia meletakkan gelas yang telah habis.
“Enggak ah, aku lihat kamu saja dari teras.” Sulastri bangkit lalu melangkah gontai, ia duduk di kursi kayu sambil memijit betis, lalu membuka ponsel sebentar dan raut wajahnya berubah, ia berjalan menyusulku.
“Kenapa berubah pikiran?” Aku tersenyum, meski ekspresi wajah Sulastri bertambah suram.
“Aku mau tanam hp-ku di sini. Orang-orang di media sosial memuakkan.” Sulastri mengambil pisau yang tertancam di salah satu pot Lidah Mertua, menggali tanah di samping rimbun bunga Euphorbia lalu mengubur ponselnya tanpa berkata-kata. Aku yang melihatnya hanya melongo. Sepuluh tahun mengenal Sulastri, aku tak bisa menebak jalan pikirannya.
Pada Minggu berikutnya, Sulastri tidak datang. Aku tak menghubunginya karena sibuk mengurus bunga-bunga di taman. Pada merekalah, kutitipkan hatiku agar bersemi setiap pagi, tak peduli hujan atau matahari, mereka menerima semua dengan lapang dada. Malam harinya, ketika hendak mematikan lampu kamar untuk tidur. Terdengar suara motor berhenti di halaman. Aku menyibak gorden, Sulastri datang dengan pakaian lengkap seperti hendak ke gunung. Jaket tebal, syal, dan kaos kaki.
“Ada apa?” aku tergesa-gesa membuka pintu. Aku mendongak menatap langit yang gelap gulita, kilat menyambar di batas cakrawala.
“Sepertinya aku diguna-guna. Sudah pasti aku diguna-guna!” suara Sulastri berkejaran dengan petir.
“Guna-guna gimana? Maksudnya kamu berguna?” Aku menarik tangan Sulastri yang dingin, mengajaknya duduk di sofa.
“Seseorang yang engga suka sama aku telah melakukan sesuatu.”
“Sesuatu apa, Sulastri?” aku mendekatkan wajah.
“Dia mengambil auraku, supaya engga ada laki-laki yang melirik. Supaya keburukan terus menimpa hidupku. Ia telah mengunci auraku, lalu kuncinya pasti telah dibuang ke laut! Aku akan mencarinya sampai ketemu.” Sulastri tak menangis, marah dan kebencian berkilat di matanya.
“Kata siapa? Kamu tahu dari mana?”
“Tadi pagi aku baru ingat, dulu waktu SMA ada teman perempuan di sekolahku yang menjadi rebutan. Dia pacaran di kelas, lalu kulaporkan ke guru dan setelah itu dia pindah sekolah karena malu. Pasti dia pelakunya. Dia membenciku setengah mati.”
Aku hampir tak percaya mendengar kalimat itu. “Sulastri, itu kejadiannya sudah dua puluh tahun yang lalu, kan?”
“Iya, tapi tidak mungkin aku begini tanpa penyebab!”
“Begini gimana? Kamu punya semuanya Sulastri, orang tua, teman-teman, pendidikan, karir.”
“Kamu engga tahu ayah ibuku selalu menuntut, sumber stres! Kamu engga tahu teman-temanku, mereka menikah, berkarir bagus, bahagia, lalu tertawa-tawa melihat nasibku. Terus apalagi, kamu bilang karir? Hari gini siapa yang mau melirik guru TK!” Suara Sulastri penuh penekanan.
“Lalu bagaimana, Sulastri?” Aku menyentuh bahunya pelan, berharap amarahnya mereda.
“Aku engga tahu harus bagaimana. Sekarang, aku hanya ingin menemukan kunci itu. Tapi aku tidak tahu di laut mana ia membuangnya.” Sulastri menangis, aku memeluk tubuhnya yang gempal. Lalu ia pamit dengan mata sembap meski telah kupaksa untuk menginap. Sulastri melambaikan tangan setelah menyalakan motor bututnya di depan gerbang kayu. Geledak petir kembali menyambar, Sulastri menghilang di balik pohon beringin besar.
Pagi buta, seseorang menggedor pintu rumahku dengan tergesa. Kusibak gorden, kupikir Sulastri, ternyata adiknya. Aku dijemput Fitri menggunakan sepeda motor, tapi ia belum berbicara sepatah kata pun. Kami melaju ke arah selatan. Ia memarkirkan motor dengan tergesa, tangannya bergetar, wajahnya pucat. Di samping motor Fitri, kulihat sekilas sepeda motor milik Sulastri. Lalu kami berjalan ke bibir pantai, tiga orang polisi, tangisan orang tua Sulastri, semua pemandangan itu membuatku lemas.
“Kamu tidak perlu mencari kunci itu ke tengah laut Sulastri, kunci itu ada di dalam dadamu.” Aku berbisik pada ombak, menitipkan kalimat terakhir yang belum sempat kusampaikan pada Sulastri.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co Gubuktulis.com
Gubuktulis.com surau.co
surau.co